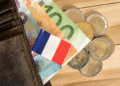Lojikata, Jakarta – Dalam pertemuan di lapangan golf Turnberry, Skotlandia pada 27 Juli 2025, Presiden Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kerangka dagang baru antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Inti kesepakatan itu adalah pengenaan tarif impor sebesar 15 % pada sebagian besar produk Uni Eropa yang masuk ke pasar AS.
Tarif 15 % ini jauh lebih rendah dibanding ancaman sebelumnya sebesar 30 %, tapi tetap meningkat pesat dari rentang tarif historis sebesar 2–5 % yang selama ini berlaku. Sektor otomotif, semikonduktor, dan farmasi juga dikenakan tarif ini, dengan pengecualian bagi beberapa barang industri strategis yang masuk ke skema “zero-for-zero”, seperti pesawat, bahan kimia tertentu, dan obat generik.
Sebagai bagian dari pertukaran kebijakan, Uni Eropa berkomitmen membeli US$ 750 miliar energi AS dalam kurun tiga tahun dan menginvestasikan US$ 600 miliar di Amerika Serikat, yang sebagian besar terkait produk industri dan peralatan militer.
Walau kesepakatan ini dianggap mencegah perang dagang besar antara dua kekuatan ekonomi dunia, para pemimpin dan ekonom Eropa menyebutnya sebagai langkah kompromi yang merugikan. Kritik tajam muncul di Jerman dan Prancis, dengan tudingan bahwa pihak UE menyerah terlalu banyak tanpa imbal ide yang setara dalam akses pasar maupun perlindungan industri nasional.
Kesepakatan ini menegaskan bahwa dalam era geopolitik perdagangan global, dominasi ekonomi sering dibangun atas landasan asimetri kebijakan. Ketika Uni Eropa rela membayar sebagian tarif, ia pun kehilangan ruang tawar dalam negosiasi digital, energi, dan logistik strategis. Bagi AS, ini kemenangan politik: membuka pasar Eropa dengan imbal balik investasi besar dan energi bersumber domestik. Namun bagi UE, ini pengingat pahit bahwa kekuatan ekonomi tak cukup jika tak disertai integritas kebijakan.
Kesepakatan ini bukan akhir dari debat dagang trans-Atlantik, melainkan awal dari masa pasca-tarif: dimana relasi industrial dan nilai politik harus dibangun kembali dengan keadilan, bukan ketidakseimbangan. Negara ketiga seperti Indonesia tidak hanya menonton, ia harus memahami bahwa struktur yang dibangun antara dua kekuatan ini akan menentukan aturan main perdagangan global masa depan. (IN/LJK)